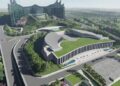Di dinding-dinding Jakarta, dari flyover sampai pos ronda, cat semprot warna-warni menjerit dua mantra: *𝗔𝗖𝗔𝗕* dan *𝟭𝟯𝟭𝟮*. Dua kode yang mungkin terdengar seperti nama geng motor atau kode voucher diskon, tapi sejatinya adalah kritik keras.
𝗔𝗖𝗔𝗕 merupakan terjemahan amarah: *𝗔𝗹𝗹 𝗖𝗼𝗽𝘀 𝗔𝗿𝗲 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗮𝗿𝗱𝘀*. Apa perlu terjemahannya? “𝗦𝗲𝗺𝘂𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘀𝗶 𝗶𝘁𝘂 𝗯𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮*”. Bahkan kini diteriaki lebih keras dengan tagar #PolisiPembunuh. Adapun angka 𝟭𝟯𝟭𝟮, juga bukan nomor togel, tapi sandi rahasia: 1=A, 3=C, 1=A, 2=B. Murid TK pun bisa menguraikannya.
Namun anehnya, di sore pengujung Agustus 2025, Presiden Prabowo lebih memilih bicara soal kesepakatan politik dengan rekan-rekan DPR ketimbang menyinggung reformasi kepolisian. Ucapannya mengalir dengan nada jenderal yang masih betah main perang-perangan.
Katanya: demo boleh, demokrasi dihargai, tapi kalau anarkis, “tindak tegas!” Titik. Masalahnya, siapa yang mendefinisikan anarkis? Apakah Affan Kurniawan —ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob 12 ton— bisa dikategorikan anarkis hanya karena ia berada di jalan yang salah?
Kalau begitu, rakyat sebaiknya mulai belajar ilmu sihir: 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘶𝘴𝘶𝘴 𝘦𝘷𝘢𝘥𝘶𝘴! —supaya bisa menghilang tiap kali berpapasan dengan polisi. Rakyat kini tak tahu lagi harus berkata apa, dan tak ngerti harus berteriak bagaimana lagi, agar polisi bisa lebih baik.
Ironi ini makin tebal ketika Kapolri dengan wajah muram meminta maaf di RSCM kepada keluarga Affan. Permintaan maaf —yang sudah jadi template, seperti ucapan “selamat berbuka” —hanya meredam sementara. Besok atau lusa, ban baja Brimob bisa saja kembali menuntaskan drama di jalanan.
Data survei Indikator Politik (2022–2023) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri anjlok hingga di bawah 50%. Ingatan warga bahwa polisi itu “𝘣𝘢𝘴𝘵𝘢𝘳𝘥” sulit dihapus, terutama pasca-Tragedi Kanjuruhan, kasus Ferdy Sambo, dan penanganan demonstrasi dengan kekerasan.
Lembaga Survei Indonesia (2024) juga mencatat persepsi bahwa Polri adalah “institusi paling korup” di Indonesia bersama DPR. Artinya, luka kepercayaan publik ini bukan insiden oknum, melainkan krisis struktural.
Ketika rakyat lebih takut pada polisi ketimbang kriminal jalanan, itu tanda alarm negara berbunyi. Coretan ACAB dan 1312 pada dinding-dinding demo itu bukan sekadar vandalisme, melainkan teks sosial —sebuah grafiti akademik, kalau mau sedikit pretensius.
Coretan itu mengajarkan bahwa rakyat sudah kehilangan bahasa resmi untuk berkomunikasi dengan penguasa. UU, pidato, hingga rapat dengar pendapat sudah tumpul. Yang tersisa hanyalah spidol permanen, cat merah, dan kaleng semprot.
Dan kalau Presiden masih terus menutup mata dan telinga terhadap kekerasan aparat, jangan salahkan rakyat bila memilih jalan aspal sebagai 𝘤𝘢𝘯𝘷𝘢𝘴 baru demokrasi. Sudah terlalu banyak catatan vandalisme pihak kepolisian terhadap rakyat.
ACAB memiliki sejarah panjang. Di Inggris 1940-an, istilah ini lahir dalam konteks perlawanan buruh tambang terhadap aparat yang melindungi eksploitasi industri. Pada 1970-an, ia dipopulerkan oleh subkultur punk, disulam di jaket-jaket denim, ditulis di tembok, dan akhirnya mendunia.
Di Amerika Serikat, frasa ini hidup kembali lewat gerakan 𝘉𝘭𝘢𝘤𝘬 𝘓𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘔𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳 yang menyorot kekerasan sistemik kepolisian terhadap warga kulit hitam. Jadi, grafiti ACAB di Jakarta bukanlah “import” mentah, tapi bagian dari kosakata global perlawanan terhadap aparat represif.
Kita bisa bercanda, menyebut ACAB sebagai singkatan lain: “Andai Cops Andai Baik.” Tapi sayangnya, kenyataan di lapangan berkata sebaliknya. Dari tragedi Kanjuruhan 2022, bentrokan Wadas, sampai Affan Kurniawan, pola yang muncul sama: aparat gemar menindas, refleksi belakangan.
Literatur kepolisian modern (David Bayley, 2001) menekankan tiga prinsip 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘪𝘤 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘤𝘪𝘯𝘨: akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik. Model 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘤𝘪𝘯𝘨 yang diterapkan di Kanada, Jepang, atau Norwegia membuktikan bahwa polisi bisa hadir sebagai mitra warga, bukan predator.
Sementara teori 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦 (Tom Tyler, 2006) menunjukkan: warga lebih patuh pada hukum bila merasa diperlakukan adil, bukan ditakut-takuti. Di negara-negara Skandinavia, polisi bahkan dipanggil “teman masyarakat”.
Di Indonesia, polisi lebih sering jadi karakter antagonis dalam meme. Ini bukan sekadar masalah citra; ini masalah nyawa. Kabar terbaru, 𝗯𝗲𝗸𝗮𝘀 𝗹𝗮𝗿𝗮𝘀 𝘀𝗲𝗽𝗮𝘁𝘂 𝗮𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗸𝗼𝗻𝗼𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗺𝗽𝗲𝗹 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝗯𝘂𝗵 𝗥𝗵𝗲𝘇𝗮 𝗦𝗲𝗻𝗱𝘆 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗮𝗺𝗮, mahasiswa yang tewas usai berdemo di Markas Polda DI Yogyakarta.
Aparat kita lebih nyaman mengandalkan gas air mata ketimbang prosedur keadilan, dengan taruhan nyawa. Dan nyawa, seperti kata filsuf Hannah Arendt, adalah satu-satunya hal yang tak bisa direvisi dalam demokrasi. Hasilnya, kepatuhan publik lahir dari rasa takut, bukan rasa percaya.
Maka, seharusnya pidato seorang Presiden bukan berhenti pada “tindak tegas.” Ia harus berani bicara “tindak adil”. Reformasi kepolisian harus masuk agenda, mesti dia ungkap jelas dalam pernyataannya, bukan hanya menekankan pembagian kue politik dengan elit Senayan.
Kalau tidak, Prabowo hanya akan dicatat sejarah sebagai Presiden yang gagah di podium, tapi gagap di lapangan. Padahal dia tahu, kualitas demokrasi tidak diukur hanya oleh pemilu bebas, tetapi juga oleh 𝘳𝘶𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘭𝘢𝘸 dan integritas aparat penegak hukum (Diamond & Morlino, 2004).
Tanpa reformasi kepolisian, demokrasi Indonesia hanya pesta demokrasi formal, tapi dalam praktiknya tetap otoritarian. Atau, dalam bahasa satir: demokrasi kita naik motor ojol, tapi bannya digilas panser.
Affan sudah pergi, diseret roda baja negara. Tapi dari darahnya lahir kembali coretan yang lebih tebal: 𝗔𝗖𝗔𝗕, 𝟭𝟯𝟭𝟮. Sebuah epitaf urban, yang entah kapan akan berhenti dicat, sebelum polisi berhenti menjadi monster dalam imajinasi rakyatnya sendiri.
#fyp #pengikut #jangkauanluas #semuaorang #AhmadieThaha #CatatanCakAT #MahadTadabburQuran #ACAB #1312 #POLISI